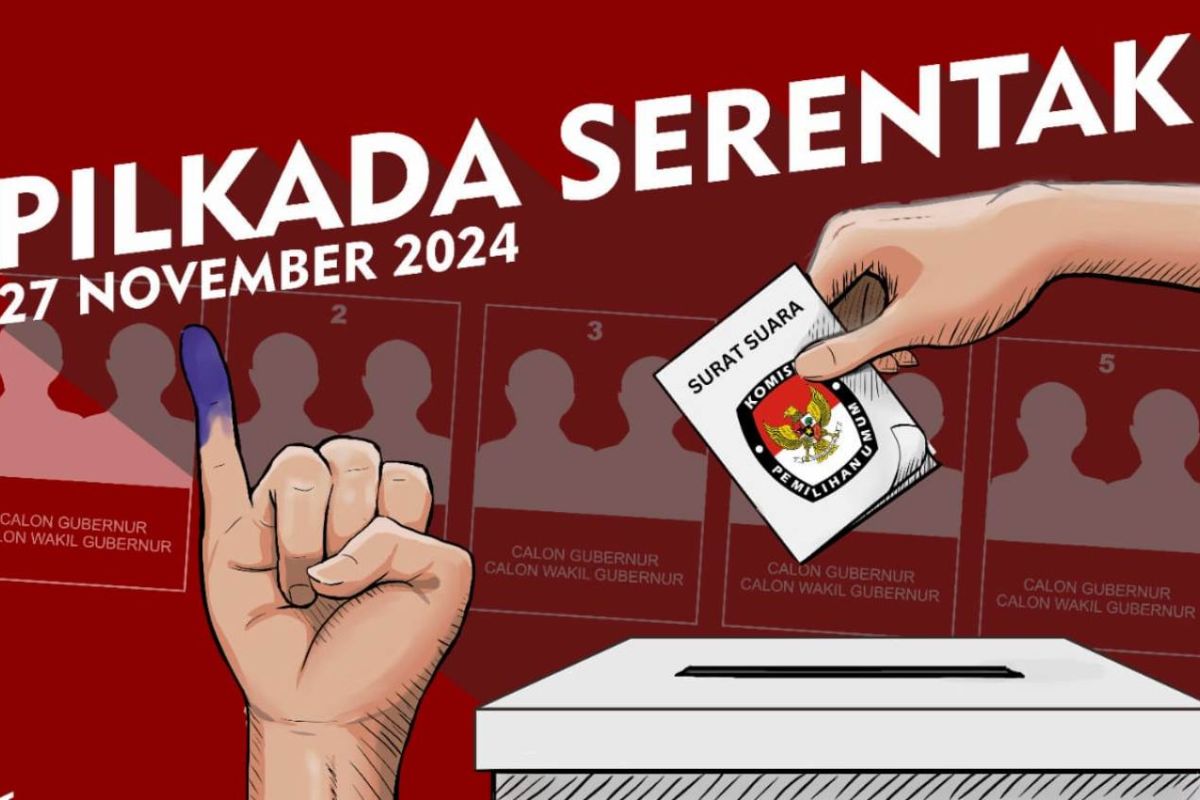
Usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD dinllai tak cocok diterapkan di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem yang berbeda.
JAKARTA - Usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD dinllai tak cocok diterapkan di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem yang berbeda.
Penegaskan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan. Menurutnya, usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak cocok diterapkan di Indonesia karena Indonesia menganut sistem yang berbeda.
Menurut Djayadi, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membandingkan sistem pilkada di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura tidak tepat karena Malaysia dan Singapura belum masuk kategori negara demokrasi.
"Ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia," kata Djayadi dalam Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang dihelat Perludem, Rabu (18/12/2024).
"Pernah diterapkan di Indonesia tahun 2000 sampai 2005, itu rakyat memilih anggota DPR. Rakyat tahu bahwa anggota DPR akan memilih kepala daerah, tapi mereka tidak tahu siapa kepala daerahnya, berasal dari mana dia," ujar dia.
Djayadi menyebutkan, Indonesia juga tidak menggunakan sistem parlementer seperti yang berlaku di Malaysia dan Singapura.
Ia mengatakan, dengan sistem parlementer, rakyat sejak awal tahu bahwa ketika mereka memilih wakil rakyat, maka para anggota Dewan itu kelak akan memilihkan orang-orang yang duduk di pemerintahan.
Djayadi juga meyakini usulan ini berpotensi menimbulkan polemik soal demokrasi Indonesia. Salah satunya, sebagai konsekuensi, maka sistem politik Indonesia akan bergeser ke arah sistem parlementer.
"Ada problem dalam artian democratic representative, kecuali kalau memang sistem kita diubah," ujar dia.
Sebelumnya, pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menganggap publik tidak boleh lupa bahwa sistem perubahan pilkada dari DPRD menjadi langsung ke tangan rakyat dilatarbelakangi oleh praktik politik uang yang tinggi, di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD untuk proses pencalonan kepala daerah (candidacy buying). Selain itu, ada masalah representasi karena kepala daerah yang dipilih DPRD dianggap tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
"Di sejumlah daerah, kantor DPRD dirusak akibat masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilihan oleh DPRD," kata Titi dirilis Kompas.com, Rabu. "Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya," sebut dia.
Menurut Titi, yang menjadi akar persoalan adalah buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai yang tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki.
"Kita seolah hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke dalam ruang-ruang tertutup di DPRD. Namun, dampaknya sangat besar, yakni kedaulatan rakyat menjadi tersandera dan masyarakat bisa semakin dijauhkan dari urusan-urusan publik," kata dia.
Titi juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membuat Putusan Nomor 55/PUU-XXII/2019 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang jangan acap kali mengubah mekanisme pemilihan langsung yang ada di Indonesia.
Sementara itu, pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa rezim pilkada dan pemilu adalah sama.
"Sehingga pilkada harus diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip pemilu juga, yaitu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, serta pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang juga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP," pungkas Titi.
 Info Detak.co | Rabu, 18 Desember 2024
Info Detak.co | Rabu, 18 Desember 2024 












