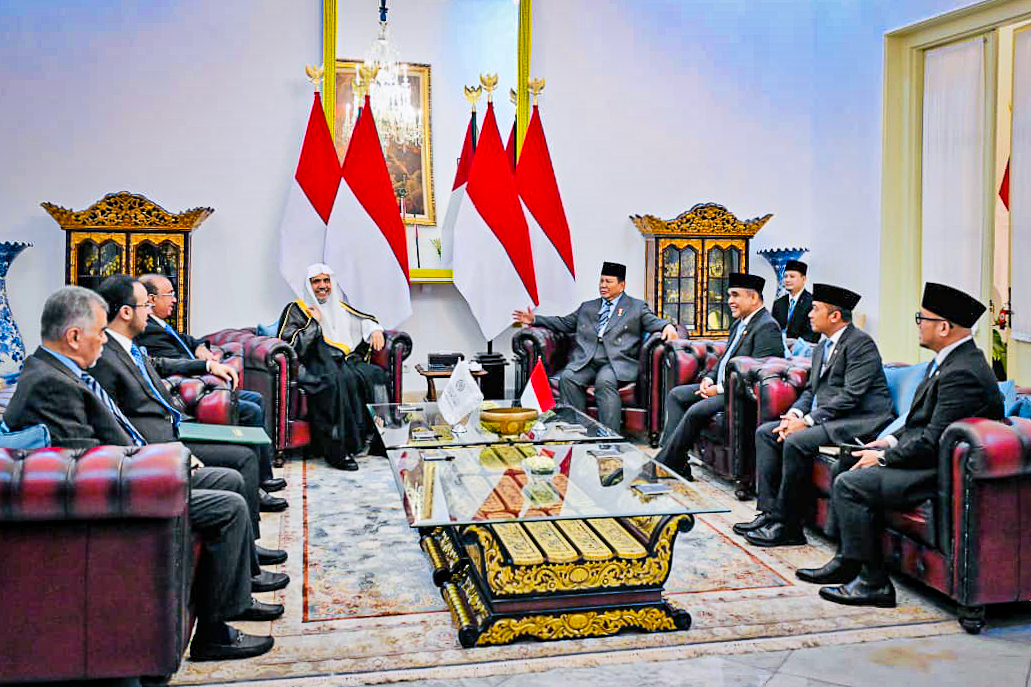Oleh: Fileski Walidha Tanjung
Malam 9 November 2025 di Alun-Alun Kota Madiun, udara terasa berbeda. Di bawah sorot lampu yang memantul pada patung Kolonel Marhadi, gema doa dan suara sastra bertemu dalam satu ruang kesadaran. Acara “Malam Refleksi Hari Pahlawan” yang diselenggarakan oleh PWI-LS Madiun Raya bukan sekadar peringatan seremonial. Ia adalah panggilan batin. Ketika saya berdiri di hadapan publik untuk membacakan puisi “Kepada yang Telah Gugur (Pahlawanku)”, saya tidak sedang berbicara tentang masa lalu yang beku, tetapi tentang luka masa kini—penjajahan yang tidak lagi datang dengan meriam dan senjata, melainkan dengan dogma dan selera budaya.
Kini, bentuk kolonialisme berubah rupa. Ia tidak lagi membawa bendera, tetapi membawa bahasa dan pakaian. Ia tidak lagi menjarah rempah, melainkan menggantikan makna dalam pikiran. Inilah penjajahan yang paling halus sekaligus paling berbahaya: penjajahan budaya yang berbalut agama, yang menempatkan kebenaran dalam satu corak tunggal dan menolak segala yang berbeda sebagai sesat. Bila dulu tanah direbut, kini yang dirampas adalah ruang berpikir dan cara beribadah; bila dulu tubuh dijajah, kini yang diperbudak adalah jiwa.
Friedrich Nietzsche pernah menulis, “Cara paling pasti untuk merusak generasi muda adalah dengan mengajarkan mereka untuk lebih menghormati orang-orang yang berpikir sama daripada mereka yang berpikir berbeda.” Petikan ini menggambarkan betapa berbahayanya homogenitas pikiran yang dipaksakan atas nama kebenaran. Di negeri yang sejatinya lahir dari keberagaman, upaya memutlakkan satu tafsir menjadi bentuk penjajahan intelektual yang nyata. Kita sedang melihat generasi yang kehilangan daya kritis karena dibius oleh keyakinan tunggal bahwa yang datang dari tradisi luar pasti lebih suci, lebih benar, lebih layak menjadi pedoman hidup.
Sebagai penyair dan pegiat budaya, kegelisahan saya berakar dari kenyataan bahwa banyak tradisi luhur Nusantara kini digerogoti oleh label “haram” dan “bid’ah”. Padahal, sebagian besar tradisi leluhur—dari slametan, tembang, hingga tari sakral—tidak pernah lahir untuk menyaingi ajaran agama. Mereka justru menjadi bentuk syukur, ungkapan spiritualitas lokal yang hidup berdampingan dengan iman. Jika Bali bisa menjadi contoh di mana agama dan budaya berkelindan seperti dua rel kereta yang sejajar, mengapa daerah lain di Nusantara justru harus menyingkirkan adatnya demi mengejar “kesalehan” versi impor?
Ketika gamelan dibungkam oleh pengeras suara yang menyalakan lagu-lagu tanpa akar budaya lokal, ketika doa-doa leluhur dianggap tidak sah karena tidak sepenuhnya berbahasa arab, kita sebenarnya sedang kehilangan jati diri bangsa. Edward Said dalam Culture and Imperialism pernah mengingatkan bahwa penjajahan tidak pernah sepenuhnya berakhir; ia hanya berubah bentuk menjadi dominasi wacana. Kini, kolonialisme hadir dalam bentuk yang lebih lembut: melalui televisi, media sosial, gaya berpakaian, bahkan tafsir keagamaan yang dikomodifikasi. Kita menyaksikan bagaimana budaya global menelan budaya lokal, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kekuasaan makna.
Namun saya percaya, kebudayaan sejati tidak bisa dimusnahkan; ia hanya bisa disembunyikan untuk sementara. Di balik nyanyian petani yang masih menyanjung bumi pertiwi, di antara nelayan yang menyebut laut dengan sebutan khas lokal, di dalam doa ibu-ibu yang menidurkan anaknya sambil bersenandung tetembangan, ada daya tahan yang tak tertaklukkan. Daya yang membuat bangsa ini tetap hidup meski diterpa badai zaman.
Puisi yang saya bacakan malam ini bukan sekadar karya sastra, melainkan ikrar. Ikrar bahwa Indonesia tidak boleh menjadi salinan dari bangsa lain. Nasionalisme sejati bukan sekadar mencintai bendera, melainkan menjaga ruh budaya yang melahirkan bendera itu. Dalam konteks ini, perjuangan melawan penjajahan gaya baru harus dimulai dari ranah budaya: dengan menulis, menari, menembang, melukis, dan memuliakan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.
Kita tidak bisa memusuhi budaya asing, sebab peradaban tumbuh dari dialog dan akulturasi. Namun kita juga tidak boleh tunduk pada hegemoni yang mematikan kebebasan ekspresi lokal. Prinsipnya sederhana: budaya asing boleh datang, tapi tidak untuk menindas. Islam datang ke Nusantara bukan dengan pedang, tetapi dengan budaya yang menghargai lokalitas. Dari sanalah Islam Nusantara lahir—lembut, toleran, dan penuh estetika. Maka ketika muncul kelompok yang berusaha “meng-Arabkan” seluruh ekspresi keagamaan di Indonesia tanpa memahami konteks sejarah dan jiwa masyarakatnya, kita perlu bertanya: apakah itu bentuk kesalehan, atau justru bentuk kolonialisme baru yang dibungkus kesucian?
Budaya adalah ingatan kolektif bangsa. Menghapusnya sama saja dengan mematikan identitas. Dalam setiap tradisi, ada kearifan ekologis, spiritual, dan sosial yang membentuk keseimbangan hidup. Menolak tradisi lokal berarti memutus rantai kebijaksanaan yang diwariskan oleh para leluhur. Disinilah pentingnya kesadaran dekolonial: menyadari bahwa kita punya hak untuk menafsirkan dunia dengan cara kita sendiri. Seperti kata Paulo Freire, “Untuk benar-benar eksis sebagai manusia adalah dengan menamai dunia, lalu mengubahnya.” Eksistensi manusia Indonesia hanya bermakna jika kita berani menamai dan mengubah dunia sesuai dengan ruh kebangsaan kita sendiri.
Dalam renungan Hari Pahlawan, saya percaya bahwa perjuangan hari ini tidak lagi soal darah dan senjata, melainkan soal makna dan kesadaran. Pahlawan masa kini adalah mereka yang menjaga keberagaman, mempertahankan bahasa ibu, dan menolak penyeragaman tafsir atas nama agama atau modernitas. Jika dulu kita berperang melawan penjajahan fisik, kini kita berperang melawan penjajahan mental dan budaya.
Namun, pertanyaannya kini: apakah kita masih memiliki keberanian untuk berpikir merdeka? Apakah kita masih mampu mendengarkan suara leluhur di tengah hiruk-pikuk globalisasi yang memekakkan? Ataukah kita diam saja, membiarkan diri dijajah oleh makna yang bukan milik kita, hingga suatu hari nanti anak-anak kita tumbuh tanpa mengenal nyanyian ibunya sendiri?
Barangkali, inilah waktu bagi kita untuk kembali menyalakan api yang dulu dijaga para pahlawan—api kesadaran, keberanian, dan kebudayaan. Sebab kemerdekaan sejati bukan hanya soal membebaskan tanah dari penjajah, tetapi juga membebaskan pikiran dari ketundukan. Dan selama nyala itu masih menyala dalam dada kita, Indonesia akan tetap hidup, tetap merdeka, dan tetap menjadi dirinya sendiri.
Berikut puisi yang saya tulis dan bacakan pada peringatan 10 November 2025
KEPADA YANG TELAH GUGUR
Wahai ruh para pahlawan,
yang telah gugur di pelukan pertiwi
tanahmu kini dijajah kembali,
bukan dengan bedil dan peluru,
namun dengan lidah, pakaian,
dan doa yang terasa asing bunyinya.
Mereka datang bukan membawa senjata,
melainkan budaya yang menyalin keyakinan,
mewarnai ibadah dengan aroma tradisi asing,
mengubah selera, mengganti makna
dari rasa cinta pada tradisi leluhur.
Kami menyaksikan,
di antara menara-menara dan pasar-pasar,
bahasa kita perlahan kehilangan lidahnya,
adat kehilangan ruhnya,
dan nama-nama leluhur
ditelan bunyi yang bukan milik kita.
Wahai pahlawan penjaga kedaulatan negeri,
dengarlah gemuruh bumi yang pernah kau bebaskan:
penjajahan kini berwajah halus,
menyusup lewat syair, gaya, dan tafsir.
Namun kami, anak cucumu, masih bersetia.
Kami menjaga nyala itu:
dari petani yang tetap menanam dengan adat budaya,
dari nelayan yang masih menyebut laut dengan bahasa ibu.
Kami berjanji, wahai pahlawan,
kami tidak akan membiarkan negeri ini
menjadi salinan dari bangsa lain.
Kami melawan penjajahan yang berbaju kesalehan,
kami menegakkan cinta yang berakar
di atas tanah air sendiri.
Karena Indonesia bukan sekadar nama,
Indonesia adalah jiwa —
jiwa yang takkan pernah dijual,
takkan disalin,
budaya asing boleh datang hidup berdampingan
namun bukan untuk memonopoli kebenaran
bukan membuat kami tunduk patuh pada padanya,
selama darahmu masih berdenyut dalam dada
wahai pahlawan, kami kan terus menjaga.
Merdeka… merdeka… merdeka.
Fileski. 9 November 2025
Fileski Walidha Tanjung adalah penulis dan penyair kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis puisi, cerpen, esai di berbagai media nasional. Buku terbarunya berjudul “Diksi Emas”.
 Info Detak.co | Minggu, 07 Desember 2025
Info Detak.co | Minggu, 07 Desember 2025