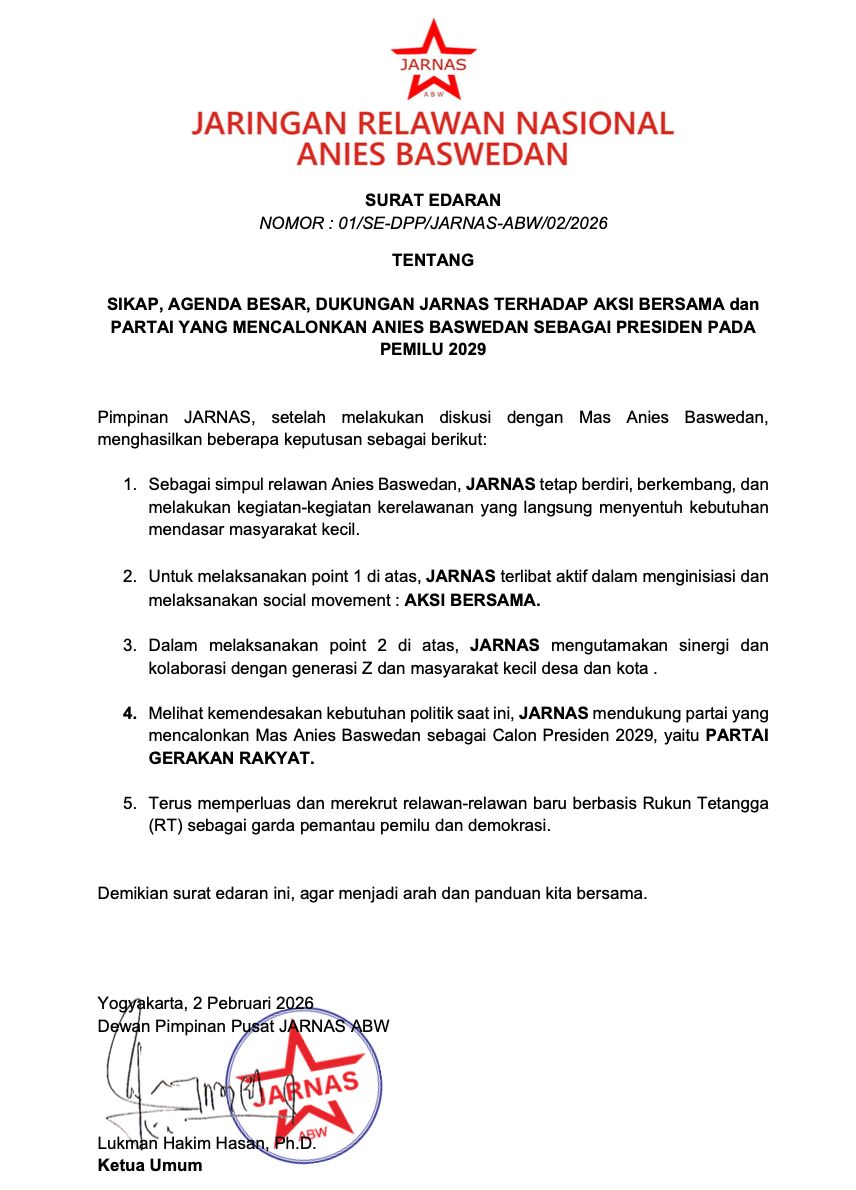Setiap tanggal 27 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Listrik Nasional sebagai momentum refleksi atas perjalanan sektor ketenagalistrikan, sektor yang diam-diam menjadi denyut utama kehidupan modern kita. Dari rumah tangga hingga industri, dari desa hingga ibu kota, listrik bukan sekadar energi, tetapi simbol kemajuan, kemandirian, dan martabat bangsa.
Tahun 2025 menjadi momen reflektif yang sangat penting. Dunia sedang berada di tengah pusaran transisi energi global, sebuah pergeseran besar dari ketergantungan pada energi fosil menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kekayaan alam yang luar biasa, tidak bisa sekadar menjadi penonton dalam babak baru peradaban energi ini.
Transisi energi bukan lagi idealisme para aktivis lingkungan, tetapi keniscayaan strategis nasional. Ia menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi, menekan emisi karbon, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memastikan masa depan pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Antara Capaian dan Realitas
Indonesia patut berbangga: rasio elektrifikasi nasional kini telah mencapai 99,8%. Hampir seluruh desa telah teraliri listrik, menandai keberhasilan besar dalam pemerataan infrastruktur dasar. Namun, keberhasilan “menyambung kabel” belum tentu berarti sistem kelistrikan kita benar-benar sehat dan tangguh.
Di balik angka gemilang itu, masih terdapat kesenjangan besar dalam kualitas pasokan. Di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara, listrik masih mengandalkan genset diesel komunal atau solar cell mandiri yang beroperasi terbatas hanya beberapa jam per hari. Ini menunjukkan bahwa pemerataan akses belum selalu diikuti oleh keandalan dan keberlanjutan.
Lebih jauh lagi, sumber energi yang menghidupi jaringan listrik nasional masih didominasi energi fosil. Data Kementerian ESDM 2025 menunjukkan, sekitar 81% pembangkitan listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara dan gas alam. PLTU batu bara masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan di Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sumatera.
Padahal, pemerintah telah menetapkan target ambisius: bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Namun realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Menurut laporan Institute for Essential Services Reform (IESR) per Juni 2025, kontribusi energi bersih baru mencapai sekitar 13–14%, didominasi oleh tenaga air dan panas bumi.
Harapan dari RUPTL Hijau
Meski demikian, ada harapan baru. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN memproyeksikan bahwa 76% kapasitas pembangkit baru akan berasal dari energi terbarukan: surya, angin, hidro, dan panas bumi. Ini merupakan arah yang patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan transformasi menuju “RUPTL hijau”.
Namun, persoalannya bukan hanya soal membangun pembangkit baru, tetapi membangun sistem yang andal dan fleksibel. Energi terbarukan, terutama surya dan angin, bersifat intermittent — tidak selalu tersedia saat dibutuhkan. Pembangkit surya hanya aktif ketika matahari bersinar, sedangkan angin bergantung pada kondisi cuaca.
Untuk itu, teknologi penyimpanan energi berskala besar (energy storage) menjadi kebutuhan mendesak. Proyek Upper Cisokan Pumped Storage (1.040 MW) di Jawa Barat yang dijadwalkan rampung tahun ini, menjadi langkah strategis. Teknologi ini memungkinkan kelebihan listrik dari pembangkit terbarukan disimpan dan digunakan saat beban puncak. Jika proyek ini berhasil, ia akan menjadi tonggak penting bagi sistem kelistrikan yang lebih tangguh dan efisien.
Namun, infrastruktur penyimpanan energi saja tidak cukup. Indonesia memerlukan jaringan transmisi lintas-pulau yang kuat untuk menghubungkan sumber daya energi terbarukan yang tersebar — dari PLTA di Kalimantan, panas bumi di Sumatera, hingga potensi surya di Nusa Tenggara — dengan pusat-pusat beban di Jawa dan Bali. Tanpa konektivitas nasional yang baik, kelebihan listrik bersih di daerah berpotensi tinggi akan tetap terisolasi.
Potensi Besar yang Belum Tergarap
Indonesia sejatinya adalah “superpower” energi terbarukan yang tertidur. Potensi tenaga surya diperkirakan mencapai lebih dari 200 GW, tenaga air sekitar 75 GW, panas bumi sekitar 28 GW, serta potensi angin dan biomassa yang terus tumbuh. Namun realisasi pemanfaatannya masih di bawah 10% dari potensi yang ada.
Penyebabnya beragam. Dari sisi regulasi, perizinan yang berbelit, ketidakpastian tarif (feed-in tariff), akses lahan yang sulit, hingga minimnya insentif fiskal membuat investor enggan menanamkan modal. Selain itu, dominasi batu bara yang masih disubsidi secara tidak langsung menciptakan ketimpangan harga energi — membuat energi bersih tampak lebih mahal di atas kertas.
Kondisi ini menjadi ironi. Di saat dunia mulai menutup PLTU dan mempercepat transisi energi hijau, Indonesia justru masih menambah proyek pembangkit batu bara dalam kapasitas tertentu, meski dengan dalih kebutuhan beban dasar.
Transisi Energi: Antara Komitmen dan Kenyataan
Pada forum internasional, Indonesia sudah menyatakan komitmennya terhadap pengurangan emisi karbon melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar. Namun hingga kini, realisasi pendanaan dan proyek-proyek turunannya berjalan lambat.
Menurut laporan terbaru IESR, untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060, Indonesia memerlukan investasi lebih dari US$ 1 triliun di sektor energi. Jumlah yang fantastis ini tentu tak bisa ditanggung hanya oleh negara atau BUMN. Dibutuhkan kemitraan lintas sektor — pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat — agar transisi energi tidak hanya berjalan, tetapi juga adil (just transition).
Artinya, peralihan dari energi fosil ke energi bersih harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pekerja di sektor batu bara, misalnya, perlu disiapkan untuk beralih ke pekerjaan baru di sektor energi hijau. Inilah makna sejati dari keadilan dalam transisi energi.
Momentum Hari Listrik Nasional 2025
Peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 tahun ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan dan potong tumpeng di kantor PLN atau ESDM. Ini harus menjadi titik balik nasional.
Kita perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah Indonesia akan terus bertahan dalam sistem lama yang murah di atas kertas tapi mahal dalam kerusakan lingkungan, atau berani melangkah menuju sistem listrik yang bersih, adil, dan mandiri?
Jawaban atas pertanyaan itu membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus berani mereformasi kebijakan energi. Dunia usaha harus membuka diri terhadap investasi hijau. Akademisi dan kampus perlu mempercepat riset energi bersih dan penyimpanan daya. Sementara masyarakat — termasuk generasi muda — harus mengambil peran aktif melalui pemanfaatan PLTS atap, penghematan energi, dan advokasi kebijakan hijau.
Tak kalah penting, literasi energi harus ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang memandang energi bersih sebagai isu gaya hidup atau wacana elit, padahal ini menyangkut hak dasar manusia untuk hidup sehat dan berkelanjutan.
Tiga langkah konkret untuk mempercepat transformasi sektor listrik nasional yang perlu diwujudkan bersama adalah sebagai berikut :
- Reformasi Kebijakan Energi
Hapus insentif bahan bakar fosil yang tidak efisien dan ubah menjadi dukungan bagi energi bersih. Permudah perizinan proyek energi terbarukan, pastikan kepastian tarif, serta dorong keterlibatan swasta dan daerah dalam pembangunan pembangkit hijau.
- Dorong Inovasi dan Investasi Teknologi Penyimpanan Energi
Selain membangun pembangkit, kita harus membangun sistem penyimpanan energi dan jaringan cerdas (smart grid) agar sistem kelistrikan lebih fleksibel, efisien, dan tangguh menghadapi gangguan.
- Libatkan Komunitas Lokal dan Generasi Muda
Transisi energi harus inklusif. Libatkan masyarakat lokal dalam proyek energi bersih, berikan ruang bagi inovator muda di bidang teknologi energi, dan jadikan kampus serta sekolah sebagai pusat edukasi energi berkelanjutan.
Penutup: Dari Retorika ke Aksi
Listrik bukan sekadar aliran energi. Ia adalah fondasi peradaban modern. Dari sinar lampu di rumah, mesin industri di pabrik, hingga server internet yang menopang dunia digital — semuanya bergantung pada sistem kelistrikan yang kuat dan bersih.
Dalam konteks krisis iklim dan ketidakpastian ekonomi global, masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola sektor listrik hari ini.
Hari Listrik Nasional 2025 harus menjadi momentum perubahan: dari retorika menuju realisasi, dari ketergantungan menuju kemandirian, dari energi kotor menuju energi yang bersih dan berkeadilan.
Kita tidak hanya membutuhkan listrik yang menyala, tetapi listrik yang menyinari masa depan — bersih, merata, dan berkelanjutan.
Oleh:
Ir. Julius Sentosa, M.T., IPM
Dosen tetap Teknik Elektro dan Pendidikan Profesi Insinyur
Universitas Kristen Petra
 Info Detak.co | Sabtu, 07 Februari 2026
Info Detak.co | Sabtu, 07 Februari 2026